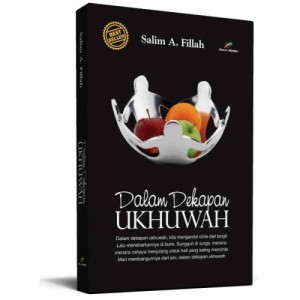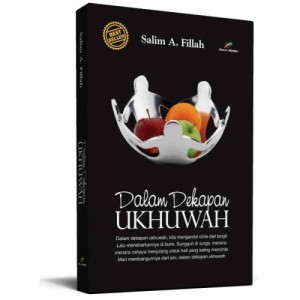
Telaga itu
luas, sebentang Ailah di Syam hingga San’a di Yaman. Di tepi telaga itu berdiri
seorang lelaki. Rambutnya hitam, disisir rapi sepapak daun telinga. Dia menoleh
dengan segenap tubuhnya, menghadap hadirin dengan sepenuh dirinya. Dia
memanggil-manggil. Seruannya merindu dan merdu. “
Marhabban ayyuhal insaan!
Silakan mendekat, silakan minum!”
Senyumnya lebar, hingga otot di ujung
matanya berkerut dan gigi putihnya tampak. Dari sela gigi itu terpancar cahaya.
Mata hitamnya yang bercelak dan berbulu lentik mengerjap bahagia tiap kali
menyambut pria dan wanita yang bersinar bekas-bekas wudhunya.
Tapi di antara alisnya yang tebal dan
nyaris bertaut itu ada rona merah dan urat yang membiru tiap kali beberapa
manusia dihalau dari telaganya. Dia akan diam sejenak. Wibawa dan akhlaqnya
terasa semerbak. Lalu dia bicara penuh cinta, dengan mata berkaca-kaca. “Ya
Rabbi”, serunya sendu, “Mereka bagian dariku! Mereka ummatku!”
Ada suara menjawab, “Engkau tak tahu
apa yang mereka lakukan sepeninggalmu!”
Air telaga itu menebar wangi yang
lebih harum dari kasturi. Rasanya lebih lembut dari susu, lebih manis dari
madu, dan lebih sejuk dari salju. Di telaga itu, bertebar cangkir kemilau
sebanyak bilangan gemintang. Dengan itulah si lelaki memberi minum mereka yang
kehausan, menyejukkan mereka yang kegerahan. Wajahnya berseri tiap kali
ummatnya menghampiri. Dia berduka jika dari telaganya ada yang dihalau pergi.
Telaga itu sebentang Ailah di Syam
hingga San’a di Yaman. Tapi ia tak terletak di dunia ini. Telaga itu Al Kautsar.
Lelaki itu Muhammad. Namanya terpuji di langit dan bumi.
***
Telaga lain yang lebih kecil, konon
pernah ada dalam cangkungan sebuah hutan di Yunani. Dan ke telaga itu, setiap
pagi seorang lelaki berkunjung. Dia berlutut di tepinya, mengagumi
bayangannya yang terpantul di air telaga. Dia memang tampan. Garis dan lekuk
parasnya terpahat sempurna. Matanya berkilau. Alis hitam dan cambang di
wajahnya berbaris rapi, menjadi kontras yang menegaskan kulit putihnya.
Lelaki itu, kita tahu, Narcissus. Dia
tak pernah berani menjamah air telaga. Dia takut citra indah yang dicintainya
itu memudar hilang ditelan riak. Konon, dia dikutuk oleh Echo, peri wanita yang
telah dia tolak cintanya. Dia terkutuk untuk mencintai tanpa bisa menyentuh,
tanpa bisa merasakan, tanpa bisa memiliki. Echo meneriakkan laknatnya di sebuah
lembah, menjadi gema dan gaung yang hingga kini diistilahkan dengan namanya.
Maka di tepi
telaga itu Narcissus selalu terpana dan terpesona. Wajah dalam air itu
mengalihkan dunianya. Dia lupa pada segala hajat hidupnya. Kian hari tubuhnya
melemah, hingga satu hari dia jatuh dan tenggelam. Alkisah, di tempat dia
terbenam, tumbuh sekuntum bunga. Orang-orang menyebut kembang itu, narcissus.
Selesai.
Tetapi Paulo
Coelho punya anggitan lain untuk kisah Narcissus. Dalam karyanyaThe
Alchemist, tragika lelaki yang jatuh cinta pada dirinya sendiri itu
diakhiri dengan lebih memikat. Konon, setelah kematian Narcissus, peri-peri
hutan datang ke telaga. Airnya telah berubah dari semula jernih dan tawar
menjadi seasin air mata.
“Mengapa kau menangis?”, tanya para
peri.
Telaga itu berkaca-kaca. “Aku
menangisi Narcissus”, katanya.
“Oh, tak heranlah kau tangisi dia.
Sebab semua penjuru hutan selalu mengaguminya, namun hanya kau yang bisa
mentakjubi keindahannya dari dekat.”
”Oh, indahkah Narcissus?”
Para peri hutan saling memandang.
“Siapa yang mengetahuinya lebih daripadamu?”, kata salah seorang. “Di
dekatmulah tiap hari dia berlutut mengagumi keindahannya.”
Sejenak hening menyergap mereka. “Aku
menangisi Narcissus”, kata telaga kemudian, “Tapi tak pernah kuperhatikan bahwa
dia indah. Aku menangis karena, kini aku tak bisa lagi memandang keindahanku
sendiri yang terpantul di bola matanya tiap kali dia berlutut di dekatku.”
***
Setiap kita punya kecenderungan untuk
menjadi Narcissus. Atau telaganya. Kita mencintai diri ini, menjadikannya pusat
bagi segala yang kita perbuat dan semua yang ingin kita dapat. Kita
berpayah-payah agar ketika manusia menyebut nama kita yang mereka rasakan
adalah ketakjuban pada manusia paling memesona. Kita mengerahkan segala daya
agar tiap orang yang bertemu kita merasa telah berjumpa dengan manusia paling
sempurna.
Kisah tentang Narcissus menginsyafkan
kita bahwa setinggi-tinggi nilai yang kita peroleh dari sikap itu adalah
ketakmengertian dari yang jauh dan abainya orang dekat. Kita menuai sikap yang
sama dari sesama, seperti apa yang kita tabur pada mereka. Dari jaraknya, para
peri memang takjub, namun dalam ketidaktahuan. Sementara telaga itu hanya
menjadikan Narcissus sebagai sarana untuk mengagumi bayangannya sendiri. Persis
sebagaimana Narcissus memperlakukannya. Pada dasarnya, tiap-tiap jiwa hanya
takjub pada dirinya.
Tetapi ‘Amr ibn Al ‘Ash merasakan
ketiadaan sikap ala Narcissus pada seorang Muhammad, lelaki yang sesampai di
surga pun masih menjadikan diri pelayan bagi ummatnya. ‘Amr telah belasan tahun
menjadikan silat lidahnya sebagai senjata paling mematikan bagi da’wah Sang
Nabi. Lalu setelah hari Hudaibiyah yang menegangkan itu, hidayah menyapanya.
Dia, bersama Khalid ibn Al Walid dan ‘Utsman ibn Thalhah menuju Madinah
menyatakan keislaman. Mereka disambut senyum Sang Nabi, dilayani bagai saudara
yang dirindukan, dimuliakan begitu rupa.
Bagaimanapun, ‘Amr merasa hanya dirinya
yang istimewa. Itu tampak dari sikap, kata-kata, dan perlakuan Sang Nabi
padanya. Hari itu dia merasa Sang Rasul pastilah mencintainya melebihi
siapapun, mengungguli apapun. Pikirnya, itu disebabkan bakat lisannya begitu
rupa yang kelak bermanfaat bagi da’wah. Terasa sekali. Maka dia beranikan diri
meminta penegasan. “Ya Rasulallah”, dia berbisik ketika kudanya menjajari
tunggangan Sang Nabi, “Siapakah yang paling kau cintai?”
Sang Nabi tersenyum. “’Aisyah”,
katanya.
“Maksudku”, kata ‘Amr, “Dari kalangan
laki-laki.”
“Ayah ‘Aisyah.” Rasulullah terus saja
tersenyum padanya.
“Lalu siapa lagi?”
“’Umar.”
“Lalu siapa lagi?”
“’Utsman.” Dan beliau terus tersenyum.
“Setelah itu”, kata ‘Amr berkisah di
kemudian hari, “Aku menghentikan tanyaku. Aku takut namaku akan disebut paling
akhir.” ‘Amr tersadar, apalagi sesudah berbincang dengan Khalid dan ‘Utsman,
bahwa Muhammad adalah jenis manusia yang membuat tiap-tiap jiwa merasa paling
dicinta dan paling berharga. Dan itu bukan basa-basi. Muhammad tak kehilangan
kejujuran saat ditanya.
Nabi itu indah dan menakjubkan memang.
Tapi yang paling menarik dari dirinya adalah bahwa berada di dekatnya
menjadikan setiap orang merasa istimewa, merasa berharga, merasa memesona. Dan
itu semua tersaji dalam ketulusan yang utuh.
***
Di buku ini, Dalam Dekapan Ukhuwah, kita
ingin meninggalkan bayang-bayang Narcissus. Kita ingin kecintaan pada diri
berhijrah menjadi cinta sesama yang melahirkan peradaban cinta. Dari Narcissus
yang dongeng, kita menuju Muhammad yang menyejarah. Pribadi semacam Sang Nabi
ini yang akan menjadi telisik pembelajaran kita. Inilah pribadi pencipta
ukhuwah, pribadi perajut persaudaraan, pembawa kedamaian, dan beserta itu
semua; pribadi penyampai kebenaran.
Tak ayal, kita
harus memulainya dari satu kata. Iman. Karena ada tertulis, yang mukmin lah yang bisa bersaudara dengan
ukhuwah sejati. Iman itu pembenaran dalam hati, ikrar dengan lisan, dan amal
dengan perbuatan. Kita faham bahwa yang di hati tersembunyi, lisan bisa
berdusta, dan amal bisa dipura-pura. Maka Allah dan RasulNya telah meletakkan
banyak ukuran iman dalam kualitas hubungan kita dengan sesama. Setidaknya,
terjaganya mereka dari gangguan lisan dan tangan kita. Dan itulah batas
terrendah dalam dekapan ukhuwah.
Dalam dekapan ukhuwah kita menghayati
pesan Sang Nabi. “Jangan kalian saling membenci”, begitu beliau bersabda
seperti dicatat Al Bukhari dalam Shahihnya, “Jangan kalian saling mendengki,
dan jangan saling membelakangi karena permusuhan dalam hati.. Tetapi jadilah
hamba-hamba Allah yang bersaudara..”
Dalam dekapan ukhuwah kita mendaki
menuju puncak segala hubungan, yakni taqwa. Sebab, firmanNya tentang penciptaan
insan yang berbangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal ditutup dengan
penegasan bahwa kemuliaan terletak pada ketaqwaan. Dan ada tertulis, para
kekasih di akhirat kelak akan menjadi seteru satu sama lain, kecuali mereka
yang bertaqwa.
Dalam dekapan ukhuwah, kita mengambil
cinta dari langit. Lalu menebarkannya di bumi. Sungguh di surga, menara-menara
cahaya menjulang untuk hati yang saling mencinta. Mari membangunnya dari sini,
dalam dekapan ukhuwah. Jadilah ia persaudaraan kita; sebening prasangka, sepeka
nurani, sehangat semangat, senikmat berbagi, dan sekokoh janji.
Dalam dekapan ukhuwah, kita akan
mengeja makna-makna itu, menjadikannya bekal untuk menjadi pribadi pencipta
ukhuwah, pribadi perajut persaudaraan, pembawa kedamaian, dan beserta itu
semua; pribadi penyampai kebenaran. Dalam dekapan ukhuwah, kita tinggalkan
Narcissus yang dongeng menuju Muhammad yang mulia dan nyata. Namanya terpuji di
langit dan bumi.
***
Ah, tapi jika
semua tadi masih terasa sulit dan melangit, mari kita sederhanakanDalam
Dekapan Ukhuwah ini dengan
sabda Muhammad Shallallaahu
‘Alaihi wa Sallam yang
menghimbau kita untuk bercermin. Seperti Narcissus. Tapi bukan di telaga. Dan
pemaknaannya pun jadi berbeda.
“Mukmin yang satu”, kata Sang Nabi,
“Adalah cermin bagi mukmin yang lain.”
Bercerminlah, tapi bukan untuk takjub
pada bayang-bayang seperti Narcissus, atau telaganya. Menjadikan sesama peyakin
sebagai cermin berarti melihat dengan seksama. Lalu saat kita menemukan hal-hal
yang tak terkenan di hati dalam bayangan itu, kita tahu bahwa yang harus kita
benahi bukanlah sang bayang-bayang. Kita tahu, yang harus dibenahi adalah diri
kita yang sedang mengaca. Yang harus diperbaiki bukan sesama yang kita temukan
celanya, melainkan pribadi kita yang sedang bercermin padanya.
Itu saja.
Selamat datang dalam dekapan ukhuwah.
Aku mencintai kalian karena Allah.